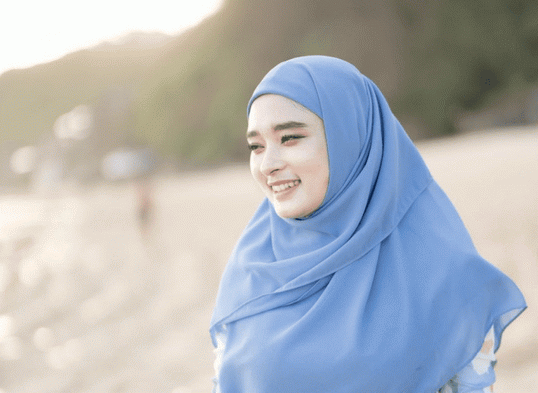“Orang labil ketemu orang labil ya jadi makin labil. Mereka saling bercermin ke temannya. Misalnya satu curhat di media sosial, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama jadi tren emosional,” ujar Kiki.
Ia mengingatkan, perilaku meniru dan konformitas sosial di kalangan remaja dapat memperkuat perasaan cemas atau sedih, apalagi bila tidak ada pendampingan dari orang dewasa. Karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan waktu mendengarkan dan memahami tanpa menghakimi.
Kiki menegaskan bahwa temuan 700 siswa dengan indikasi gangguan kesehatan mental sebaiknya menjadi peringatan tentang kebutuhan pendampingan psikologis di sekolah, bukan dasar untuk melabeli mereka sebagai “anak bermasalah”.
“Remaja itu sangat dinamis, bisa berubah cepat. Bukan berarti kalau mereka merasa sedih atau stres lalu pasti gangguan mental. Yang mereka butuh itu teman bercerita, bukan stigma,” tegasnya.
BACA JUGA: Tepuk Sakinah Viral, Psikolog: Bukan Jaminan Cegah Perceraian, Inti Pernikahan Tetap Komunikasi
Ia juga mendorong sekolah untuk membuka layanan konseling psikologis secara rutin dan menciptakan budaya yang ramah kesehatan mental, agar siswa merasa aman untuk berbagi cerita tanpa takut dicap “aneh” atau “sakit jiwa”.
Menurut Kiki, fase remaja memang rawan ketidakstabilan emosi, dan pendampingan yang empatik jauh lebih dibutuhkan daripada label “gangguan mental”.
Ia mengingatkan masyarakat bahwa pergi ke psikolog bukan berarti seseorang gila atau sakit, melainkan bagian dari menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental. (*)
Editor: Farah Nazila